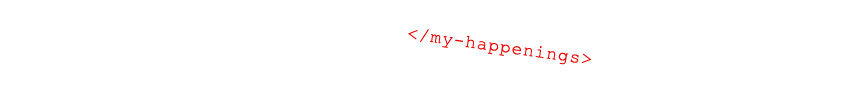do we need heroes?siang tadi aku dikirimi url radio free asia versi bahasa burma yg memuat wawancaraku dengan seorang reporternya ttg pramoedya ananta toer. wawancara ttg pram ini merupakan satu bagian dari serial mereka yg bertajuk "asian heroes."
wawancara per telepon 2 minggu lalu itu dimulai dengan pretensi bahwa pramoedya ananta toer adalah seorang pahlawan. at least, si pewawancara tdk lagi meragukan hal tsb. tapi dalam kepalaku malah muncul pertanyaan: apa yg membuat seseorang menjadi pahlawan?
soon the answer unfolds. yg mewawancara bertanya mengapa pram dipenjara oleh belanda, oleh pemerintah sukarno, kemudian soeharto. kujawab, soal mengapa pram masuk penjara bukit duri thn 1947-9 aku tdk tau jelas, tetapi aktifitasnya di kantor berita jepang domei mungkin berhubungan dgn itu. utk alasan pram dipenjara kemudian dibuang oleh pemerintah orba, semua sdh tau, termasuk si pewawancara. tetapi, fokus pertanyaan pada victimization, apalagi dlm konteks heroisme, segera menunjukkan tanda2 bhw yg membuat orang menjadi pahlawan adalah penderitaan (injury), atau tepatnya menjadi korban sebuah otoritas (victimization).
kalau victimization adalah kondisi untuk menjadi pahlawan, maka tdk bisa diingkari bhw rejim orba telah secara tdk langsung membuat pram menjadi hero. itu sebabnya pram tdk takut pada pemerintah. saat dia berkunjung ke amerika thn 1999 yg lalu, pada kami di ithaca, pram bercerita bhw dia sama sekali gak takut bakal dicekal. bahkan, katanya, bila dicekal, dia malah bisa bikin "ribut." keributan yg dimaksud adl kesempatan mengumumkan pd dunia bhw victimization terhadap dirinya msh terus berlanjut. ucapan ini bukan berarti pram mengharapkan injury dr otoritas. tetapi jelas menunjukkan kesadarannya, bhw on the other side of injury and victimization, there is heroization. krn dengan begitu perhatian orang akan terarah kepadanya, begitu juga simpati mereka.
percakapan lewat telepon yg superficial ttg pram lantas berubah menjadi filosofis. kepada si pewawancara, aku malah balik bertanya: what is a hero? what makes one a hero? and why do we have heroes? membahas ini, percakapan kami menjadi serius, tapi sayang sdh melenceng dr garis besar program mereka, yaitu menampilkan seorang pahlawan dr asia. oleh karena itu, segmen ini menjadi konsumsi kami berdua saja.
di akhir maret 1965, lewat surat edaran departemen pendidikan dan kebudayaan 23/3-1965 No. 4063/S dan 25/3-1965 No. 4255/S, sejumlah buku dilarang beredar di sekolah2 di indonesia. yg masuk black list adalah buku2 dari kelompok yg berlawanan ideologi dng kelompok pram yg beraliran sosial realisme. oleh mereka yg berideologi kiri, kelompok humanisme universal dianggap kaki tangan budaya barat. kelompok pram memang garang, yg berlawanan ideologi hendak dibabat. sementara kedekatan aidit dengan soekarno seperti memberi angin pada mereka.
kita semua tau apa yg terjadi 6 bulan kemudian, sesudah september 1965. panggung politik terbalik, yg kiri malah yg habis terbabat. mereka yg buku2nya dilarang pd bulan maret, malah naik panggung. sedangkan pram dkk ditangkapi, dipenjara, diasingkan ke pulau buru, dan buku2nya menjadi terlarang. hb jassin, yg bukunya masuk black list pd bulan maret, karena perubahan politik, naik tahta menjadi paus sastra indonesia. oleh karena itu kita belajar periodisasi sastra indonesia dr jassin, bukan dr bakri siregar. dan oleh krn itu juga, buku pelajaran sastra kita sunyi ttg sastrawan2 yg dicap "kiri" spt tan malaka, marco kartodikromo, semaoen, juga pram sendiri.
kalau sdh begini, terlihat bhw "hero" adalah hasil konstruksi dari historical accidents (kecelakaan/kebetulan sejarah). saya sebut kecelakaan krn kalau saja G30S dan witch hunts thdp komunisme tdk terjadi, yg bakal dianggap villain (penjahatnya) adl pram dkk, sedangkan hero-nya mungkin jassin dkk. bukankah kubu pram juga mencekal dan menekan lawan2 ideologi mereka?
sekarang ini banyak orang menokohkan pram secara obsesif. bahkan ada sekelompok anak muda yg memuja pram bagaikan sebuah cult. yg berani mengkritik pram bakal dimaki habis2an, dituduh antek manikebu, orba, dsb. mereka otoriter dlm berinterpretasi, persis spt orba, persis spt kelompok pram saat berada di atas angin, juga spt kelompok oposisi pram yaitu para seniman di jaman orba yg puluhan tahun tutup kuping, tutup mulut melihat sesama seniman ditindas. pram memang pantas dikagumi utk tulisan2nya yg bagus, juga utk keberaniannya. tapi pram perlu juga ditempatkan pada konteksnya, yaitu pertentangan ideologi dari dua kelompok yg sama2 mencoba menjadi otoritas dlm mendefinisikan sastra indonesia.
kembali pada pertanyaan di atas: apakah kita butuh seorang pahlawan? kalau setiap pahlawan lahir dari pertentangan dan kekerasan -- i think we can live without them. selain itu, setiap bentuk pemujaan adalah penghambaan pada sebuah struktur dan ideologi. lantas kenapa mau menghambakan diri? aku jadi teringat pada soundtrack film
mad max yg dinyanyikan oleh tina turner (available in the jukebox). lagu yg bersentimen anti perang tersebut lebih dari meneriakkan jawabanku:
we don't need another hero
we don't need to know the way home
all we want is life beyond
the thunderdome
kemarin, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, matahari bersinar cerah di kota berkeley. sudah berhari-hari aku kehabisan bahan makanan, tapi ogah keluar karena hujan. wilayah california tengah sedang dilanda musim hujan yg paling hebat dalam 125 tahun terakhir. praktis sepanjang bulan maret kemarin, hanya 4 hari yg tdk diguyur hujan. padahal california justru terkenal dengan murahnya sinar matahari.
kemarin, gerbang selatan kampus (sather gate) yg selama ini
deserted menjadi ramai dengan mahasiswa. yg berdemo, yg jualan, yg sdg survey, yg berorasi, yg main musik, bahkan yg main barongsai. aku sampai tertawa geli melihat sekelompok mahasiswa ABC (american-born chinese) yg saling gendong memainkan 2 macan barongsai. penonton yg lain pun tersenyum.

senyum menjadi murah saat matahari bersinar cerah. sepatu boots dan payung, untuk hari ini bisa ditanggalkan. berganti dengan sandal dan t-shirt lengan pendek yg sudah lama menanti gilirannya. saking happy-nya moodku, aku gak keberatan ketika didekati seorang mahasiswa yg sedang survey ttg kehidupan kampus. kujawab semua pertanyaannya dengan sabar.
dari kampus, aku singgah sebentar di apartment utk mengganti celana jeans dengan short dan sendal jepit. finally, pikirku, aku bisa belanja makanan hari ini. dengan langkah santai aku menelusuri college street menuju safeway. seolah turut merayakan munculnya dewi matahari, bunga2 sakura di sepanjang jalan pun mekar penuh. begitu juga bunga2 daffodil di halaman rumah orang. aku berjalan dengan langkah ringan, senyum tersungging di bibir. alangkah manisnya bagian kota ini!
tiba di perempatan elmwood shopping, kudapati seorang opa tua bertopi dan bertongkat, sedang mempromosikan kumpulan puisinya. dia punya beberapa set kumpulan puisi yang entah hendak dibagikan cuma2, atau hendak dijual. dengan suara ramah dia menyapa semua yang lewat, "do you read poetry?" rata2 menggeleng dengan sopan.
tiba giliranku lewat di depannya, aku pun disapa dengan pertanyaan yang sama. dengan ramah pula kujawab, "sorry, i don't." ternyata jawabanku mengecewakan si opa, karena dengan nada menyesal doi berucap, "oh, you broke my heart!" mendengar ucapannya, dengan nada serius tapi dengan senyum bandel aku membalas, "i know! it breaks my heart too!"
orang2 di sekitar kami, yg sedang menunggu lampu merah berganti hijau, terkekeh mendengar perkataanku. tidak terkecuali si opa. memang orang2 bisa dengar percakapan kami. mendengar ucapanku yg terakhir, beberapa orang menoleh, mencari lihat siapa gadis dengan omongan yg gak masuk akal tadi. begitu melihat aku dan si opa sdg terkekeh, senyum mereka jadi lebih lebar.
sinar matahari yang hangat, yang akhir2 ini menjadi langka di berkeley, telah membawa
mood gembira pada semua orang. nikmatilah sinar matahari selagi bisa, mungkin begitu pikir mereka. karena memang sih, yang bisa kita nikmati setiap hari sering terlupa nilainya. biasanya kita baru sadar telah kehilangan di saat sesuatu yg "biasa" itu tak lagi ada.
Tjap TjayTulisan Goenawan Mohamad tentang bahasa Indonesia yang dimuat di majalah
Tempo minggu ini (10-16 April 2006, berjudul "Gado-gado") menarik untuk ditanggapi.
Dalam tulisannnya, beliau memuji bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa yang mempersatukan, tetapi juga yang mendukung kebhinnekaan Indonesia.
Untuk klaim yang pertama, saya kira tidak bisa dibantah kebenarannya. Tetapi untuk yang ke dua, mari kita pikirkan lagi.
Apakah bahasa Indonesia itu? Atau lebih tepatnya, apakah batasan-batasannya?
Jaman sekarang ini, seorang anak sekolah bisa dengan spontan menjawab pertanyaan tersebut. Dia bisa bertutur bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti yang diajarkan di sekolah, ataupun merujuk pada berbagai teks -- sastra maupun bukan -- yang dianggap mewakili bahasa Indonesia.
Tetapi bagaimana bentuknya ketika bahasa ini baru dikoinasi pada Kongres Pemuda ke II tahun 1928?
Dua tahun sebelumnya, pada Kongres Pemuda yang pertama, draft Sumpah Pemuda masih menuliskan bahwa bahasa persatuan adalah "bahasa Melajoe," bukan bahasa Indonesia. Atas permintaan Sanusi Pane, bahasa Melayu tersebut digantikan dengan "bahasa Indonesia."
Tetapi, dari sekian banyak variasi bahasa Melayu, yang manakah yang pada waktu itu naik pangkat menjadi bahasa nasional kita? Bukan apa-apa, bahasa Melayu orang Papua lumayan mirip dengan yang dipakai di Manado, tetapi berbeda dengan yang dipergunakan di Makassar ataupun Sumatra. Selain itu, ada bahasa Melayu versi Tionghoa yang ramai dipergunakan oleh masyarakat urban dan terbitan-terbitan di jaman itu. Semua dialek Melayu ini tak berbatas jelas, tanpa ejaan atau struktur yang mengikat, apalagi buku tata bahasa.
Pada akhirnya intelektual-intelektual Indonesia Muda (meminjam istilah St. Takdir Alisjahbana) yang menentukan bentuk dan batasan bahasa Indonesia. Bukan kebetulan kalau mereka ini adalah produk dari institusi-institusi budaya pemerintah kolonial Belanda. Selain lulusan sekolah pemerintah, kebanyakan mereka berafiliasi dengan Balai Pustaka. Dan bukan rahasia lagi bahwa kedua institusi ini -- sekolah untuk
inlander dan Balai Pustaka -- adalah alat pemerintah kolonial untuk mempropagandakan bahasa Melayu yang standar.
Alhasil, yang kemudian tampil sebagai bahasa Indonesia adalah sebentuk bahasa Melayu yang sopan, kaku, dengan berbagai pembakuan yang membekukan. Peraturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di jaman Orba hanyalah kelanjutan dari proses standardisasi bahasa Indonesia. Deraan pembakuan/pembekuan bahasa ini bahkan mendorong Benedict Anderson untuk menulis
beberapa usulan demi pembebasan bahasa Indonesia (
Tempo, 6 Januari 2002).
Belenggu bahasa Indonesia, menurut Anderson, telah membuat orang menjadi buta huruf terhadap sastra pra-Orba. Sastra Melayu Tionghoa yang begitu kaya dan berwarna, telah dilupakan dan sulit untuk dibangkitkan kembali. Sebabnya adalah orang Indonesia sekarang telah tidak biasa dengan bahasa yang ramai, dinamis, dan "tanpa aturan" ini. Penerbitan kembali tulisan jurnalis Kwee Thiam Tjing (Tjamboek Berdoeri),
Indonesia dalem Api dan Bara, dalam bahasa aslinya, mengundang keluhan dari sebagian orang. Bahasa dan ejaannya membuat kepala mumet, kata mereka.
Pada pertumbuhannya, bahasa Indonesia memang mengorbankan bahasa Melayu pasar atau Melayu Tionghoa yang lama malang-melintang di dunia percetakan Hindia Belanda. Dalam edisi pertamanya sesudah Dai Nippon angkat kaki dari bumi nusantara,
Malang Post (5 November 1946), seperti terbitan-terbitan Tionghoa lain yang baru berani beroperasi lagi, mengumumkan maksudnya untuk mulai menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tulis editornya, naskah-naskah yang hendak dimasukkan supaya ditulis dalam bahasa Indonesia.
Niat untuk mengadopsi bahasa nasional boleh jadi muncul dari semangat nasionalisme yang menghanyutkan di masa revolusi. Tapi mungkin juga dari ketakutan dianggap tidak nasionalis jika tidak berganti bahasa.
Tidak cuma bahasa Melayu Tionghoa, tetapi sastra daerah pun harus mundur teratur demi pertumbuhan bahasa Indonesia. Sesudah Balai Pustaka dinasionalisasi di awal kemerdekaan, terbitan-terbitan dalam bahasa daerah diberhentikan secara total. Mereka hendak berkonsentrasi penuh pada terbitan bahasa Indonesia. Segenap otot budaya perlu dikerahkan untuk nation-building, alasan H. B. Jassin (
Surat-surat).
Dan Jassin memang benar. Berkat bahasa Indonesia, orang Manado bisa berkomunikasi dengan orang Madura. Berkat bahasa Indonesia juga, kita tidak lagi mempertanyakan apakah bangsa Indonesia itu benar-benar ada atau hanya sebuah konstruksi abstrak yang justru menemukan bentuknya lewat berbagai atribut seperti bahasa, sastra, sensus, museum, peta, dan pelajaran sekolah.
Sebab bahasa tidak cuma menunjukkan bangsa, tetapi terlebih dahulu ia menciptakannya.
Dan di antara sekian banyak keuntungan yang kita nikmati dari bahasa nasional kita, patut direnungkan pula hal-hal yang terkubur karenanya. Pakar linguistik dari Cornell University, John Wolff, pernah mengatakan bahwa hal yang menyedihkan dari kisah sukses bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah matinya berbagai bahasa suku. Di Filipina, kebalikannya, absennya bahasa nasional secara tidak langsung melanggengkan bahasa-bahasa daerah dan suku.
Romantisme dan nada
celebratory yang ditawarkan Goenawan Mohamad dalam menyikapi bahasa Indonesia memang bisa dimaklumi. Terlebih di saat di mana konsepsi negara kesatuan sedang dipertanyakan dan diperjuangkan kembali. Tetapi bentuk persatuan yang mengorbankan cita rasa kedaerahan, mentabukan warna kesukuan, atau memurtadkan aroma etnis, pantas untuk direnungkan kembali. Karena sisi lain dari mata uang ini adalah munculnya anggapan bahwa suatu kelompok atau daerah yang mengancam keutuhan negara layak untuk dikorbankan. Sudah saatnya paradigma kebangsaan yang revolusioner ini dilepaskan. Yang kita perlukan sekarang adalah pemahaman kebangsaan sebagai sebuah tekad, sebuah kesepakatan untuk bersama.
"Tunding LSM Provokator Papua, Intelijen Nggak Cerdas"kalimat tsb adalah judul
sebuah artikel di rakyat merdeka yg aku baca pagi ini. membaca judul tsb, aku jadi ngakak. kalimatnya mengingatkan aku pada film
renaissance man yg dibintangi danny devito. filmnya berkisah ttg seorang bill rago (played by devito) yg sdg diterpa berbagai masalah besar secara beruntun -- dipecat dari kerjaan, kemudian perceraian dengan istri. oleh unemployment office dimana rago minta kerjaan, dia ditawarkan utk mengisi lowongan mengajar sastra dan critical thinking pada anak2 remaja yg baru direkrut di sebuah sekolah militer. kegusaran rago thdp kesialan hidupnya makin bertambah ketika dia mendapati bhw anak2 yg harus dididiknya adalah segerombolan pemuda dengan berbagai latar belakang gelap spt kemiskinan, broken home, school drop-out, bekas gangster, pemusik yg gagal, bahkan pemuda kampung dengan pemikiran yg sangat rasis.

judul di atas mengingatkan aku pada suatu episode di film tsb ketika rago mengajarkan konsep "oxymoron" sebagai sebuah gaya bahasa.
"oxymoron adalah sebuah gaya bahasa yang menggabungkan dua kata yg pada prinsipnya memiliki makna yg bertolak belakang," terang rago pada sebuah sesi di kelasnya.
para calon serdadu yg menjadi siswanya menatap bengong karena sulit menangkap konsep tsb. salah seorang di antaranya mengacungkan tangan dan bertanya, "bisakah anda memberi contoh bagaimana bentuk oxymoron itu?"
"contohnya seperti frase 'military intelligent'," tandas rago dengan dongkol.
aku menonton film ini mungkin ada 10 tahun yg lalu, tapi episode di atas membekas di kepalaku krn membuat aku ngakak. bukan rahasia lagi bahwa pada umumnya military recruits bukanlah dari anak2 yg cerdas. seperti yg digambarkan di
renaissance man, kebanyakan mereka putus sekolah, pengangguran, bekas gangster, bekas pecandu, dsb. di mata masyarakat sipil spt si tokoh rago, adalah sangat menjengkelkan bhw orang2 "sampahan" seperti ini yg kemudian menjadi wakil2 otoritas, sebagai tentara ataupun polisi. karena itu bentuk majemuk "military intelligent" baginya adalah sebuah lelucon, kalau bukan sebuah oxymoron.
dengan alasan yg hampir sama aku tertawa membaca judul artikel
rakyat merdeka di atas. kalau rago menertawakan "military" yg mengaku "intelligent," aku terlebih lagi tertawa karena badan intelijen kita di indonesia ternyata "nggak cerdas," alias kurang intelijen. hahaha... mungkin di sinilah salah satu titik benang kusut dalam kehidupan bernegara di indonesia -- yaitu intelijen yg kurang cerdas. sehingga ketika terjadi masalah spt yg di abepura itu, mereka bukannya mencari akar kemarahan orang papua thdp otoritas, tapi malah menyalahkan LSM sbg yg memprovokasi. ini seperti segerombolan perampok yg menyatroni rumah orang, tapi ketika harus menghadapi amukan pemilik rumah, malah menyalahkan tetangga yg membangunkan pemilik rumah dan membisiki bhw rumahnya sedang dirampoki.